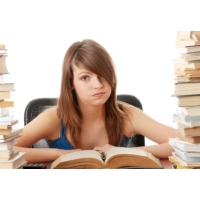BAB I
TINJAUAN TEORITIS
A. PENGERTIAN KOMUNIKASI
Komunikasi adalah proses pertukaran perasaan, keinginan, kebutuhan dan pendapat (Mv Cubbin & Dhal, 1985). Galvin dan Brommel (1986), mendefinisikan komunikasi keluarga sebagai suatu simbiosis, proses transaksional menciptakan dan membagi arti dalam keluarga. Seperti halnya setiap orang mempunyai gaya komunikasi yang berbeda, begitu pula setiap keluarga mempunyai gaya dan pola komunikasi yang unik dan berbeda. Komunikasi yang jelas dan fungsional antara keluarga merupakan alat yang penting untuk mempertahankan lingkungan yang kondusif yang diperlukan untuk mengenbangkan perasaan berharga dan harga diri serta menginternalisasikannya. Sebaliknya, komunikasi yang tidak jelas diyakini sebagai penyebab utama fungsi keluarga yang buruk ( Holman,1983; Satir,1983; Satir, Bannem Gerber & Gomori, 1991). Masalah komunikasi yang problematis dalam keluarga terjadi dimana-mana. Watzlawic dan rekan (1967), peneliti komunikasi keluarga memperkirakan bahwa 85% dari semua pesan yang dikirim dalam keluarga adalah salah paham.
B. UNSUR KOMUNIKAS
pola dan proses komunikasi merupakan salah satu proses informasi dalam keluarga yang konsisten dengan kerangka system secara umum. Komunikasi memerlukan pengirim, saluran dan penerima pesan serta interaksi antara pengirim dan penerima. Pengirim adalah orang yang mencoba untuk memindahkan suatu pesan kepada orang lain. Penerima adalah sasaran dari pengirim pesan . bentuk atau saluran adalah rute pesan. Komunikasi diteruskan dari kognisi atau pikiran pengirim melalui ruang ke kognisi penerima. Modalitas komunikasi yang dibahas secara luas di literatur mencakup pembicaraan, tulisan, dan media seperti televisi atau internet. Modalitas komunikasi yang ditulis dalam literature komunikasi interpersonal dan komunikasi keluarga adalah bahasa yang digunakan. Akan tetapi, banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga yang tidak yang tidak dapat (memilih atau tidak) sepenuhnya berpartisipasi secara penuh dalam modalitas komukasi oral atau pendengaran ( mis, ibu yang dapat mendengar dengan anak tunarungu, oaring tua dengan anak yang dapat mendengar, orang tua yang mengalami gangguan pendengaran dengan cucunya.
Interaksi dalam arti yang lebih luas mengacu pada pengiriman dan penerimaan pesan, termasuk respon yang ditimbulkan oleh pesan terhadap penerima dan pengirim. Interksi bersipat dinamik, merupakan perubahan komunikasi secara konstan diantara individu (Watzlawick, Beavin, & Jackson,1976). Pesan yang diawali oleh pengirim selalu didistorsi baik oleh pengirim, maupun penerima. salah satu poenyebab utama distorsi adalah kecemasan diri individu yang berinteraksi, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Penyebab yang biasa terjadi lainnya adalah perbedaan dalam kerangka acuan dari individu yang berinteraksi, karena tidak ada persamaan seperti perbedaan usia, latar belakang etnik atau jenis kelamin. Dalam interaksi sehari-hari anggota keluarga biasanya mengasumsikan bahwa anggota keluarga yang lain mempunyai kerangka acuan yang sama kerena hal ini tidak benar untuk banyak kasus, sehingga kesalahpahaman terjadi.
C. PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI
Watzlawick dan rekan (1967), dalam tulisan seminar mereka tentang komunikasi keluarga, Pragmatis of Human Communication, menetapkan enam prinsip komunikasi yang menjadi dasar untuk memehami proses komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi tersebut adalah:
1. Prinsip pertama dan yang paling terpenting yaitu suatu pernyataan bahwa tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi, karena semua prilaku adalah komunikasi. Pada setiap situasi ketika terdapat dua orang atau lebih, individu mungkin atau tidak mungkin berkomunikasi secara verbal. Dalam konteks ini, komunikasi nonverbal merupakan ekspresi tanpa bahasa seperti membalikkan badan atau mengerutkan kening, tapi bukan merupakan bahasa isyarat.
2. Prinsip kedua dari komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai dua tingkat yaitu informasi (isi) dan perintah (instruksi). Isi yaitu apa yang sebenarnya sedang dikatakan (bahasa verbal) sedangkan instruksi adalah menyampaikan maksud dari pesan (Goldenberg,2000). Isi suatu pesan dapat saja berupa pernyataan sederhana, tetapi mempunyai meta-pesan atau instruksi bergantung pada variabel seperti emosi, dan alur bicara, gerakan dan posisi tubuh serta nada suara.
3. Prinsip ketiga (Watzlawick et al.,1967) berhubungan dengan “ pemberian tanda baca (pungtuasi) “ (Bateson, 1979) atau rangkaian komunikasi. Komunikasi melibatkan transaksi, dan dalam pertukaran tiap respon berisi komunikasi berikutnya, selain riwayat hubunbgan sebelumnya (Hartman & Laird, 1983). Komunikasi melayani sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan dan proses penataan diri dlam keluarga.
4. Prinsip komunikasi yang keempat diuraikan oleh Watzlick dan rekannya (1979) yaitu terdapat dua tipe komunikasi yaitu digital dan analogik. Komunikasi digital adal;ah komunikasi verbal ( bahasa isyarat) yang pada dasrnya menggunakan kata dengan pemahaman arti yang sama. Jenis komunikasi yang kedua, analogik yaitu ide atau suatu hal yang dikomunikasikan, dikirim secara nonverbal dan sikap yang representative (Hrtman & Laird, 1983). Komunikasi analogik dikenal sebagai bahasa tubuh, ekspresi tubuh, ekspresi wajah, irama dan nada kata yang diucapkan (isyarat) berbagai manifestasi nonverbal lainnya (non-bahasa)byang dapat dilakukan oleh seseorang( watzlick et al, hal 62).
5. Prinsip komunikasi kelima diuraikan oleh kelompok yang sama dari beberapa ahli teori komunikasi keluarga (Watzlick, Beavin, & Jackson, 1967) yang disebut prinsip redundasi (kemubaziran). Prinsip ini merupakan dasr pengembangan penelitian keluarga yang menggunakan keterbatasan pengamatan interaksi keluarga sehingga dapat memberikan penghayatan yang valid kedalam pola umum komunikasi
6. Prinsip komunikasi yang keenam diuraikan oleh Batson dan rekan (1963) adalah semua interaksi komunikasi yang simetris atau komplementer. Polka komunikasi simetris, prilaku pelaku bercermin pada prilaku pelaku interaksi yang lainnya. Dalam komunikasi komplementer, prilaku seorang pelaku interksi melengkapi prilaku pelaku interaksi lainnya. Jika satu dari dua tipe komunikasi tersebut digunakan secara konsisten dalam hubungan keluarga, tipe komunikasi ini mencerminkan nilai dan peran serta pengaturan kekuasaan keluarga.
D. PROSES KOMUNIKASI FUNGSIONAL
Menurut sebagian besar terpi keluarga, komunikasi fungsional dipandang sebagia landasan keberhasilan, keluarga yang sehat (Watzlick & Goldberg, 2000) dan komunikasi fungsional didefinisikan sebagai pengiriman dan penerima pesan baik isi maupun tingkat instruksi pesan yang lansung dan jelas (Sells,1973), serta sebagi sasaran antara isi dan tingkat instruksi. Dengan kata lain komunikasi fungsional dan sehat dalam suatu keluarga memerlukan pengirim untuk mengirimkan maksud pesan melalui saluran yang reltif jelas dan penerima pesan mempunyai pemahaman arti yang sama dengfan apa yang dimaksud oleh pengirim (Sells). Proses komunikasi fungsional terdiri dari beberapa unsur, antara lain :
1. Pengiriman Fungsional
Satir (1967) menjelaskan bahwa pengiriman yang berkomunikasi secara fungsional dapat menyatakan maksudnya dengan tegas dan jelas, mengklarifikasi dan mengualifikasi apa yang ia katakan, meminta umpan balik dan terbuka terhadap umpan balik.
a. Menyatakan kasus dengan tegas dan jelas
Salah satu landasan untuk secara tegas menyatakan maksud seseorang adalah penggunaan komunikasi yang selaras pada tingkat isi dan instruksi (satir,1975).
b. Intensitas dn keterbukaan.
Intensitas berkenaan dengan kemampuan pengirim dalam mengkomunikasikan persepsi internal dari perasaan, keinginan,dan kebutuhan secara efektif dengan intensitas yang sama dengan persepsi internal yang dialaminya. Agar terbuka, pengirim fungsional menginformasikan kepada penerima tentang keseriusan pesan dengan mengatakan bagaimana penerima seharusnya merespon pesan tersebut.
c. Mengklarifikasi dan mengualifikasi pesan
Karakteristik penting kedua dari komunikasi yang fungsional menurut Satir adalah pernyataan klarifikaasi daan kualifikaasi. Pernyataan tersebut memungkinkan pengirim untuk lebih spesifik dan memastikan persepsinya terhadap kenyataan dengan persepsi orang lain.
d. Meminta umpan balik
Unsur ketiga dari pengirim fungsional adalah meminta umpan balik, yang memungkinkan ia untuk memverifikasi apakah pesan diterima secara akurat, dan memungkinkan pengirim untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi maksud.
e. Terbuka terhadap umpan balik
Pengirim yang terbuka terhadap umpan balik akan menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, bereaksi tanpa defensive, dan mencoba untuk memahami. Agar mengerti pengirim harus mengetahui validitas pandangan penerima. Jadi dengan meminta kritik yang lebih spesifik atau pernyataan “memastikan”, pengirim menunjukkan penerimaannya dan minatnya terhadap umpan balik.
2. Penerima Fungsional
Penerima fungsional mencoba untuk membuat pengkajian maksud suatu pesa secara akurat. Dengan melakukan ini, mereka akan lebih baik mempertimbangkan arti pesan dengan benar dan dapat lebih tepat mengkaji sikap dan maksud pengirim, serta perasaan yang diekspresikan dalam metakomunikasi. Menurut Anderson (1972), penerima fungsional mencoba untuk memahami pesan secara penuh sebelum mengevaluasi.ini berarti bahwa terdapat analisis motivasi dan metakomunikasi, serta isi. Informasi baru, diperiksa dengan informasi yang sudah ada, dan keputusan untuk bertindak secara seksama dioertimbangkan. Mendengar secara efektif, member umpan balik, dan memvalidasi tiga tekhnik komunikasi yang memungkinkan penerima untuk memahami dan merespons pesan pengirim sepenuhnya.
a. Mendengarkan
Kemampuan untuk mendengar secara efektif merupakan kualitas terpenting yang dimiliki oleh penerima fungsional. Mendengarkan secara efektif berarti memfokuskan perhstisn penuh pada seseorang terhadap apa yang sedang dikomunikasikannya dan menutup semua hal yang aakan merusak pesan. Penerima secara penuh memperhatikan pesan lengkap dari pengirim bukan menyalahartikan arti dari suatu pesan. Pendengar pasif merespons dengan ekspresi datar dan tampak tidak peduli sedangkan pendengar aktif dengan sikap mengomunikasikan secara aktif bahwa ia mendengarkan. Mengajukan pertanyaan merupakan bagian penting dari mendengarkan aktif (Gottman, Notarius, Gonso dan Markman, 1977). Mendengarkan secara aktif berarti menjadi empati, berpikir tentang kebutuhan, dan keinginan orang lain, serta menghindarkan terjadinya gangguan alur komunikasi pengirim.
b. Memberikan umpan baliki
Karakteristik utam kedua dari penerima funbgsional adalah memberikan umpan balik kepada pengirim yang memberitahu pengirim bagaimana penerima menafsirkan pesan. Pernyataan ini mendorong pengirim untuk menggali lebih lengkap. Umpan balik juga dapat melalui suatu proses keterkaitan, yaitu penerima membuat suatu hubungan antara pengalaman pribadi terdahulu (Gottman et.al, 1877) atau kejadian terkait dengan komunikasi pengirim.
c. Member validasi
Dalam menggunakan validasi penerima menyampaikan pemahamannya terhadap pemikiran dan perasaan pengirim. Validasi tidak berarti penerima setuju dengan pesan yang dikomunikasikan pengirim, tetapi menunjukan penerimaan atas pesan tersebut berharga.
E. PROSES KOMUKASI DISFUNGSIONAL
1. Pengirim Disfungsional
Komunikasi pengirim disfungsional sering tidak efektif pada satu atau lebih karakteristik dasar dari pengirim fungsional. Dalam menyatakan kasus, mengklarifikasi dan mengkulifikasi, dalam menguraikan dan keterbukaan terhadap umpan balik. Penerima sering kali ditinggalkan dalam kebingungan dan harus menebak apa yang menjadi pemikiran atau perasaan pengirim pesan. Komunikasi pengirim disfungsional dapat bersifat aktif atau defensif secara pasif serta sering menuntut untuk mendapatkan umpan balik yang jelas dari penerima. Komunikasi yang tidak sehat terdiri dari :
a. Membuat asumsi
Ketika asumsi dibuat, pengim mengandalkan apa yang penerima rasakan atau pikiran tentang suatu peristiwa atau seseorang tanpa memvalidasi persepsinya. Pengirim disfungsional biasanya tidak menyadari asumsi yang mereka buat, ia jarang mengklarifikasi isi atau maksud pesaan sehingga dapat terjadi distorsi pesan. Apabila hal ini terjadi, dapat menimbulkan kemarahan pada penerima yang diberi pesan, yang pendapat serta perasaan yant tidak dianggap.
b. Mengekspresika perasaan secara tidak jelas
Tipe lain dari komunikasi disfungsional oleh pengirim adalah pengungkapan perasaan tidak jelas, karena takut ditolak, ekspresi perasaan pengirim dilakukan dengan sikap terselubung dan sama sekali tertutup. Komunikasi tidak jelas adalah “sangat beralasan” (Satir, 1991) apabila kata-kata pengirim tidak ada hubunganya dengan apa yang dirasakan. Pesan dinyatakan dengan cara yang tidak emosional. Berdiam diri merupakan kasus lain tentang pengungkapan perasaan tidak jelas. Pengirim merasa mudah tersinggung terhadap penerima yang tetap tidak mengungkapkan kemarahannya secara terbuka atau mengalihkan perasaannya ke orang atau benda lain.
c. Membuat respon yang menghakimi
Respon yang menhakimi adalah komunikasi disfungsional yang ditandai dengan kecenderungan untuk konstan untuk menbgevaluasi pesan yang menggunakan system nilai pengirim. Pernyataan yang menghakimi selalu mengandung moral tambahan. Pesan pernyataan tersebut jelas bagi penerima bahwa pengirim pesan mengevaluasi nilai dari pesan orang lain sebagai “benar”, atau “salah”, “baik” atau “buruk”, “normal” atau “tidak normal”.
d. Ketidakmampuan untuk mendefinisika kebutuhan sendiri
Pengirim disfungsional tidak hanya tidak mampu untuk menekspresikan kebutuhangnya. Namun juga karena takut ditolak menjadi tidak mampu mendefenisikan prilaku yang ia harapkan dari penerima untuk memenuhi kebutahan mereka.sering kali pengirim disfungsiopnal tidak sadar merasa tidak berharga, tidak berhak untuk mengungkapkan kebutuhan atau berharap kebutuhan pribadinya akan dipenuhi.
e. Komunikasi yang tidak sesuai
Penampilan komunikasi yang tidak sesuai merupakan jenis komunikasi yang disfungsional dan terjadi apabila dua pesan yang bertentangan atau lebih secara serentak dikiri (Goldenberg, 2000). Penerima ditinggalkan dengan teka-teki tentang bagaimana harus merespon. Dalam kasus ketidaksesuaian pesan verbal dan nonverbal, dua atau lebih pesan literal dikirim secara secara serentak bertentangan satu sama lain. Pada ketidaksesuaian verbal nonverbal pengirim mengkomunikasikan suatu pesan secara verbal, namun melakukan metakomunikasi nonverbalyang bertentangan dengan pesan verbal. Ini biasanya diketahuinsebagai “pesan campuran”, misalnya “ saya tidak marah pada anda” diucapakan dengan keras, nada suara tinggi dengan tangan menggempal.
2. Penerima Disfungsional
Jika penerima disfungsional, terjadi komunikasi yang terputus karena pesan tidak diterima sebagaimana dimaksud, karena kegagalan penerima untuk mendengarkan, atau menggunakan diskualifikasi. Merespon secara ofensif, gagal menggali pesan pengirim, gagal memvalidasipesan, merupakan karakterstik disfungsional lainnya.
a. Gagal untuk mendengarkan
Dalam kasus gagal untuk mendengarkan, suatu pesan dikirim, namun penerima tidak memperhatikan atau mendengarkan pesan tersebut. Terdapat beberapa alasan terjadinya kegagalan untuk mendengarkan, berkisar dari tidak ingin memerhatikan hingga tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Hal ini biasanya terjadi karena distraksi, seperti bising, waktu yang tidak tepat, kecemasan tinggi, atau hanya karena gangguan pendengaran.
b. Menggunakan diskualifikasi
Penerima disfungsional dapat menerapkan pengelakkan untuk mendiskualifikasi suatu pesan dengan menghindari isu penting. Diskualifikasi adalah respon tidak langsung yang memungkinkan penerima untuk tidak menyetujui pesan tanpa memungkinkan penerima untuk tidak menyetujui pesan tanpa benar-benar tidak menyetujuinya.
c. Menghina
Sikap ofensif komunikasi menunjukkan bahwa penerima pesan bereaksi secara negatif, seperti sedang terancam. Penerima tampak bereaksi secara defensif terhadap pesan yang mengasumsikan sikap oposisi dan mengambil posisi menyerang. Pernyataan dan permintaan dibuat dengan konsisten dengan sikap negatif atau dengan harapan yang negatif.
d. Gagal menggali pesan pengirim
Untuk mengklarifikasi maksud atau arti dari suatu pesan, penerima fungsional mencari penjelasan lebih lanjut. Sebaliknya, penerima disfungsional menggunkan respon tanpa menggali, seperti membuata asumsi , memberikan saran yang prematur, atau memutuskan komunikasi.
e. Gagal memvalidasi pesan
Validasi berkenaan dengan penyampaian penerimaan penerima. Oleh karena itu, kurangnya validasi menyiratkan bahwa penerima dapat merespon secara netral atau mendistorsi dan menyalahtafsirkan pesan. Mengasumsikan bukan mengklarifikasi pemikiran pengirim adalah suatu contoh kurangnya validasi.
3. Pengirim dan Penerima Disfungsional
Dua jenis urutan intearksi komunikasi yang tidak sehat, melibatkan baik pengirim maupun penerima, juga secara luas didiskusikan dalam literatur komunikasi. Komunikasi yang tidak sehat merupakan kominikasi yang mencerminkan pembicaraan “ parallel” yang menunjukan ketidakmampuan untuk memfokuskan pada suatu isu.
Dalam pembicraan parallel, setiap individu dalam interaksi secara konstan menyatakan kembali isunya tanpa betul-beetul mendengarkan pandangan orang lain atau mengenali kebutuhan orang lain. Orang yang berinteraksi disfungsional, mungkin tidak mampu untuk memfokuskan pada satu isu. Tiap individu melantur dari satu isu ke isu lain bukannya menyelesaikan satu masalah atau meminta suatu pengungkapan.
F. POLA KOMUNIKASI FUNGSIONAL DALAM KELUARGA
1. Berkomunikasi Secara Jelas dan Selaras
Pola sebagian nkeluarga yang sehat, terdapat keselarasan komunikasi diantara anggota keluarga. Keselarasan merupakan bangunan kunci dalam model komunikasi dan pertumbuhan menurut satir. Keselarasan adalah suatun keadaan dan cara berkomunikasi dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika keluarga berkomunikasi dengan selarad terdapat konsistensi dengan selaras terdapat konsistensi anatara tingkat isi dan instruksi kominikasi. Apa yang sedang diucapkan, sama dengan isi pesan. Kat-kata yang diucapkan, perasaan yang kita ekspresikan, dan prilaku yang kita tampilkan semuanya konsisten. Komunikasi pada kelurga yang sehat merupakan suatu proses yang sangat dinamis dan saling timbal balik. Pesan tidak hanya dikirim dan diterima.
2. Komunikasi Emosional
Komunikasi emosional berkaitan dengan ekspresi emosi dan persaan dari persaan marah, terluka, sedih, cemburu hingga bahagia, kasih sayingdan kemesraan (Wright & Leahey, 2000). Pada keluarga fungsional perasaan anggota keluarga ddiekspresikan. Komunikasi afektif pesan verbal dan nonverbal dari caring, sikapfisik sentuhan, belaian, menggandeng dan memandang sangat penting, ekspresi fisik dari kaisih saying pada kehidupan awal bayi dan anak-anak penting untuk perkembangan respon afektif yang normal. Pola komunikasi afeksi verbal menjadi lebih nyata dalam menyampaikan pesan afeksional, walaupun pola mungkin beragam dengan warisan kebudayaan individu.
3. Area Komunikasi Yang Terbuka dan Keterbukaan diri
Keluarga dengan pola komunikasi fungsional menghargai keterbukaan, saling menghargai perasaan, pikiran, kepedulian, spontanitas, autentik dan keterbukaan diri. Selanjutnya keluarga ini mampu mendiskusikan bidang kehidupan isu personal, social, dan kepedulian serta tidak takut pada konflik. Area ini disebut komunikasi terbuka. Dengan rasa hormat terhadap keterbukaan diri. Satir (1972) menegaskan bahwa anggota keluarga yant terus terang dan jujur antar satu dengan yang lainnya adalah orang-orang yang merasa yakin untuk mempertaruhkan interaksi yang berarti dan cenderung untuk menghargai keterbukaan diri (mengungkapkan keterbukaan pemikiran dan persaan akrab).
4. Hirarki Kekuasaan dan Peraturan Keluarga
System keluarga yang berlandaskan pada hirarki kekuasaan dan komunikai mengandung komando atau perintah secara umum mengalir kebawah dalam jaringan komunikasi keluarga. Interaksi fungsional dalam hirarki kekuasaan terjadi apabila kekuasaan terdistribusi menurut kebutuhan perkembangan anggota keluarga (Minuchin, 1974). Apabila kekuasaan diterpkan menurut kemampuan dan sumber anggota keluarga serta sesuai dengan ketentuan kebudayaan dari suatu hubungan kekuasaan keluarga.
5. Konflik dan Resolusi Konflik Keluarga
Konflik verbal merupakan bagian rutin dalam interaksi keluarga normal. Literature konflik keluarga menunjukkan bahwa keluraga yang sehat tanpak mampu mengatasi konflik dan memetik mamfaat yang positif, tetapi tidak terlalu banyak konflik yang dapat mengganggu hubungan keluarga. Resolusi konflik merupakan tugas interaksi yang vital dalam suatu keluarga (Vuchinich,1987). Orang dewasa dalam kelurga perlu belajar untuk mengalami konflik konstruktif. Walaupun orang dewasa menyelesaikan konflik dengan berbagai cara , resolusi konflik yang fungsional terjadi apabila konflik tersebut dibahas secara terbuka dan strategi diterpkan untuk menyelesaikan konflik dan ketika orang tua secara tepat menggunakan kewenangan mereka untuk mengakhiri konflik.
G. POLA KOMUNIKASI DISFUNGSIONAL DALAM KELUARGA
Komunikasi disfungsional didefinisikan sebagai transmisi tidak jelas atau tidak langsung serta permintaan dari salah satu keluarga. Isi dan instruksi deari pesan dan ketidaksesuaian antara tingkat isi dan instruksi dari pesan. Transmisi tidak lansung dari suatu pesan berkenaan dari pesan yang dibelokkan dari saran yang seharusnya kepada orang lain dalam keluarga. Transmisi langsung dari suatu pesan berarti pesan mengenai sasaran yang sesuai. Tiga pola komunikasi yang terkait terus menerus menyebabkan harga diri rendah adalah egasentris, kebutuhan akan persetujuan secara total dan kurangnya empati.
1. Egosentris
Individu memfokuskan pada kebutuhan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain, perasaan atau perspektif yang mencirikan komunikasi egosentris. Dengan kata lain, anggota keluarga yang egosentris mencari sesuatu dari orang lain untuk memenuhu kebutuhan mereka. Apabila individu tersebut harus memberikan sesuatu, maka mereka akan melakukan dengan keengganan, dan rasa permusuhan,defensive atau sikap pengorbanan diri, jadi tawar-menawar atau negosiasi secara efektif sulit dilakukan, karena seseorang yang egosentris meyakini bahwa mereka tidak boleh kalah untuk sekecil apapun yang mereka berikan.
2. Kebutuhan Mendapatkan Persetujuan Total
Nilai keluarga tentang mempertahankan persetujuan total dan menghindari konflik berawal ketika seseorang dewasa atau menikah menetukan bahwa mereka berada satu sama lain, walaupun perbedaan yang pasti mungkin sulit untuk dijelaskan seperti yang diekspresikan dalam pendapat, kebiasaan, kesukaan atauhrapan mungkin terlihat sebagai ancaman kerena ia dapat mengarah pada ketidaksetujuan dan kesadaran bahwa mereka merupakan dua individu yang terpisah
3. Kurang Empati
Keluarga yang egosentris tidak dapat menteloransi perbedaan dan tidak akan mengenal akibat dari pemikiran, persaan dan perilaku mereka sendiri terhadap anggota keluarga yang lain. Mereka sangat terbenam dalam pemenuhan kebutuhan mereka sendiri saja bahwa mereka tidak mampu untuk berempati. Dibalik ketidakpedulian ini, individu dapat menderia akibat perasaan tidak berdaya. Tidak saja mereka tidak menghargai diri mereka sendiri tapi mereka juga tidak menghargai oaring lain. Hal ini menimbulakan suasana tegang, ketakutan atau menyalahkan. Kondisi ini terlihat pada komunikasi yang lebih membingungkan, samar, tidak langsung, terselubung dan defensif bukan memperlihatkan keterbukaan, kejelasan dan kejujuran.
4. Area Komunikasi Yang Tertutup
Keluarga yang fungsional memiliki area komunikasi yang terbuka, keluarga yang sedikit fungsional sering kali menunjukkan area komunikasi yang semakin tertutup. Keluarga tidak mempunyai peraturan tidak tertulis tentang subjek apa yang disetujui atau tidak disetujui untuk dibahas. Peraturan tidak tertulis ini secara nyata terlihat ketika anggota keluarga melanggar peraturan dengan membahas subjek yang tidak disetujui atau mengungkapkan perasaan yang terlarang.
H. KOMUNIKASI DALAM KELUARGA DENGAN GANGGUAN KESEHATAN
Istilah gangguan kesehatan berkenaan dengan setiap perubahan yang mempengaruhi proses kehidupan klien (psikologis, fisiologis, social budaya, perkembangan dan spiritual) (Carpeniyo, 2000). Gangguan dalam status kesehatan sering kali mencakup penyakit kronis dan penyakit yang mengancam kehidupan serta ketidakmampuan fisik dan mentak akut atau kronik, namun dapat juga meliputi perubahan dalam area ksehatan lainnya. Pola Temuan penelitian tentang adaptasi keluarga terhadap penyakit kronik dan mengancam kehidupan secara konsisten menunjukkan bahwea factor sentral dalam fungsi keluarga yang sehat adalah terdapatnya keterbukaan, kejujuran, dan komunukiasi yang jelas dalam mengatasi pengalaman kesehatan yang menimbulkan stres serta isu terkait lainnya (Khan,1990;Spinetta & Deasy-Spineta, 1981). Jiak keluarga tidak membahas isu penting yang dihadapi mereka, akan menyababkan jarak emosi dalam hubungan keluarga, dan meningkatnya stress keluarga (Friedman, 1985; Walsh,1998). Sters yang meningkat mempengaruhi hubungan keluarga dan kesehatan keluarga serta anggotanya (Hoffer, 1989).
1. Area Pengkajian
Pernyataan berikut ini harus dipertimbangkan ketika menganalisis pola komunikasi keluarga.
a. Dalam mengobservasi keluarga secara utuh atau serangkaian hubungan keluarga, sejauh mana pola komunikasi fungsional dan disfungsional yang digunakan ?. diagram pola komunikasi sirkular yang terjadi berulang. Selain membuat diagram pola komunikasi sirkular, prilaku spesifik berikut ini harus dikaji:
1) Seberapa tegas dan jelas anggota menyatakan kebutuhan dan perasaan interaksi?
2) Sejauh mana anggota menggunakan klerifikasi dan kualifikasi dalam interaksi?
3) Apakah anggoata keluarga mendapatkan dan merespon umpan balik secara baik, atau mereka secara umumtidak mendorong adanya umpan balik dan penggalian tentang suatu isu?
4) Sebera baik anggota keluarga mendengarkan dan memperhatikan ketika berkomunikasi?
5) Apakah anggota mencari validasi satu sama lain?
6) Sejauh mana anggota menggunakan asumsi dan pernyataan yang bersifat menghakimi dalam interksi?
7) Apakah anggota berinterksi dengan sikap menhina terhadap pesan?
8) Seberapa sering diskualifikasi digunakan?
b. Bagimana pesan emosional disampaikan dalam keluarga dan subsistem keluarga?
1) Sebera sering pesan emosional disampaikan?
2) Jenis emosi apa yang dikirimkan ke subsistem keluarga? Apakah emosi negatif, positif, atau kedua emosi yang dikirimkan?
c. Bagaimana frekuensi dan kualitas komunikasi didalam jaringan komunikasi dan rangkaian hubungan kekeluargaan?
1) Bagaimana cara/sikap anggota kelurga (suami-istri, ayah-anak,anak-anak) saling berkomunikasi?
2) Bagaimana pola pesan penting yang biasanya? Apakah terdapat perantar?
3) Apakah pesan sesuai dengan perkembangan usia anggota?
d. Apakah pesan penting keluarga sesuai dengan isi instruksi ? apabila tidak, siapa yang menunjukkan ketidaksesuaian tersebut?
e. Jenis proses disfungsional apa yang terdapat dalam pola komunikasi keluarga?
f. Apa isu penting dari personal/keluarga yang terbuka dan tertutup untuk dibahas?
g. Bagiman factor-faktor berikut mempengaruhi komunikasi keluarga?
1) Konteks/situasi
2) Tahap siklus kehidupan kelurga
3) Latar belakakang etnik kelurga
4) Bagaimana gender dalam keluarga
5) Bentuk keluarga
6) Status sosioekonomi keluarga
7) Minibudaya unik keluarga
2. Diagnosa Keperawatan Keluarga
Masalah komunikasi keluarga merupakan diagnosis keperawatn keluarga yang sangat bermakna, Nort American Diagnosis Assosiation (NANDA) belum mengidentifikasi diagnosis komunikasi yang berorientasi keluarga. NANDA menggunakan perilaku komunikasi sebagai bagian dari pendefisian karakteristik pada beberapa diagnosis mereka;seperti proses berduka disfungsional salah satu diagnosis keperawatn yang terdapat dalam daftar NANDA adalah “hanbatan komunikasi verbal”, yang berfokus pada klien individu yang tidak mampu untuk berkomunikasi secara verbal. Giger & Davidhizar (1995) menegaskan bahwa ”hambatan komunikasi verbal” tidak mempertimbangkan kjebudayaan klien sehingga secara kebuyaan tidak relevan dengan diagnosis keperawatan.
3. Intervensi Keperawatan Keperawatan
Intervensi keperawatn keluarga dalam keluarga dalam area komunikasi terutama melibatkan pendidikan kesehatan dan konseling, serta kolaborasi sekunder, membuat kontrak, dan merujuk ke kelompok swa-bantu, organisasi komunitas, dan klinik atau kantor terapi keluarga. Model peran juga berperan tipe pemberian pendidikan kesehatan yang penting. Model peran melalui observasi anggota keluarga mengenai tenaga kesehatan keluarga dan bagaimana mereka berkomunikasi selam situasi interaksi yang berbeda bahwa mereka belajar meniru perilaku komunikasi yang sehat.
Konsling dibidang komunikasi keluarga melibatkan dorongan dan dukungan keluarga dalam upaya mereka untuk meningkatkan komunikasi diantara mereka sendiri. Perawat keluarga adalah sebagai fasilitator proses kelompok dan sebagi narasumber. Wright dan Leahey (2000) menklasifikan tentang tiga intervensi keluarga secara lansung (berfokus pada tingkat kognitif, afektif, dan perilaku dari fungsi) membantu dalam pengorganisasian srategi komunikasispesifik yang dapat diterapkan, strategi intervensi dalam masing-masing ketiga domain meliputi pendidikan kesehatan dan konsling.
a. Intervensi keperawatn keluarga dengan focus kognitif memberikan atau ide baru tentang komunikasi. Informasi adalah opendidikan yang dirancang untuk mendorong penyelesaian masalah keluarga. Apakah anggota mengubah perilaku komunikasi mereka pertama sangat bergantung pada bagiamana mereka mempersepsikan masalah. Wright & Laehey (2000) menegaskan peran penting dari persepsi dan keyakinan.
b. Intervensi dalam area afektif diarahkan pada perubahan ekspresi emosi anggota keluarga baik dengan meningkatkan maupun menurunkan tingkat komunikasi emosional dan modifikasi mutu komunikasi emosional. Tujuan keperawatan spesifik didalam konteks kebudayaan keluarga, membantu anggota keluarga mengekspresikan dan membagi perasaan mereka satu sama lain sehingga:
1) Kebutuhan emosi mereka dapat disampaikan dan ditanggapi dengan lebih baik.
2) Terjadi komunikasi yang lebih selaras dan jelas
3) Upaya penyelesaian masalah keluarga difasilitasi.
c. Intervensi keperawatan keluarga berfokus pada perilaku, perubahan perilaku menstimulasi perubahan dalam persepsi “realitas” anggota keluarga dan persepsi menstimulasi perubahan perilaku (proses sirkular, rekursif). Oleh karena itu, ketika perawat keluarga menolong anggota keluarga belajar cara komunikasi yang lebih sehat. Ia juga akan membantu anggota keluarga untuk mengubah persepsi mereka atau membangun realitas tentang suatu situasi.
Intervensi pendidikan kesehatan dan konsling dirancang untuk mengubah komunikasi keluarga meliputi;
a. Mengidentifikasi keinginan perubahan perilaku spesifik anggota keluarga dan menyusun rencana kolaboratif untuk suatu perubahan
b. Mengakui, mendukung, dan membimbing anggota keluarga ketika mereka mulai mencoba untuk berkomunikasi secar jelas dan selaras.
c. Memantau perubhan perilaku yang telah menjadi sasran sejak pertemuan terdahulu. Tanyakan bagimana perilaku komunikassi yang baru, apakah ada masalah yang terjadi, serta jika mereka mempunyai pertanyaan atau hal penting tentang perubahan tersebut.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Komunikasi keluarga dikonsepsulisasikan sebagai salah satu dari empat dimensi struktur dan system keluarga beserta kekuasaan, peran dan pengambilan keputusan, serta dimensi struktur nilai. Struktur keluarga dan proses komunikasi terkait memfasilitasi pencapaian fungsi keluarga. Selain itu, pola komunikasi dalam sisten keluarga mencerminkan peran dan hubungan anggota keluarga. Komunikasi memerlukan pengirim, saluran dan penerima pesan serta interaksi antara pengirim dan penerima. Pengirim adalah seorang yang mencoba untuk memindahkan suatu pesan yang dikirimkan dan saliran merupakan perjalanan atau rute pesan.
Enam prinsip komunikasi adalah: (1) tidak mungkin untuk tidak berkomuniasi; semua perilaku adalah komunikasi; (2) komunikasi mempunyai dua tingkat yaitu komando dan informasi; (3) komunikasi melibatkan proses transaksional dan tiap anggota keluarga mempunyai “pungtuasi” peristiwa interaksi mereka sendiri; (4) ada dua tipe komunikasi yaitu digital dan analogik; (5) interaksi keluarga adalah redundansi yaitu interaksi keluarga dalam kisaran perbatas dari urutan perilaku berulang-ulang; (6) semua interaksi komunikasi simetris atau saling melengkapi.
Komunikasi fungsional didefinisikan sebagi pengiriman dan penerimaan tingkat isi dan instruksi dari tiap pesan yang jelas dan langsung begitu pula keselarsan antara tingkat isi dan instruksi. Komunikasi disfungsional adalah pengiriman dan penerimaan isi dan instruksi pesan yang tidak jelas dan tidak langsung atau tidak ada kesesuaian antara tingkat isi dan instruksi.
Karakteristik keluarga yang sehat adalah komunikasi yang jelas dan kemampuan untuk saling mendengarkan. Komunikasi yang baik diperlukan untuk membina dan memlihara hubungan penuh rasa cinta. Factor sentral dalam fungsi keluarga yang sehat ketika seseorang mengalami perubahan kesehatan adalah komunikasi yang terbuka, jujur. Jelas dalam mengatasi pengalamankesehatan yang menimbulkan sters serta isu terkait. Pedoman pengkajian komunikasi keluarga digambarkan sebagai pedoman untuk diagnosis dan intervensi keperawatan untuk memfasilitasi pola komunikasi sehat keluarga.
B. Saran
Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa menggunakan makalah ini dan juga menjadikannya sebagai pedoman dalam memberikan intervensi keperawatan tentang komunikasi pada keluarga dengan gangguan masalah kesehatan dan dalam memberikan pendidikan serta konslinguntuk merubah perilaku .
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan senantiasa mengaharapkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Tak lupa salawat dan salam bagi junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis masih diberi kesehatan dan umur sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul ”KOMUNIKASI KELUARGA” yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keperawatan Keluarga. Dalam penyusunan makalah ini penulis sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan mungkin jauh dari sempurna, begitupun dengan makalah ini oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta kepada pembaca pada umumnya.
Pekanbaru, April 2011
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komunikasi keluarga dinyatakan dalam bentuk konsep sebagai salah satu dari empat dimensi struktur system keluarga, kekuasaan, pengambilan keputusan dan struktur peran serta norma dan nilai keluarga. Dimensi tersebut saling berhubungan dan saling bergantung secara erat. Karena keluarga merupakan suatu sistem social, terdapat interaksi dan umpsn balik bersinambungan antar lingkungan internal dan eksternal. Perubahan pada satu bagian system keluarga pada umumnya diikuti dengan perubahan kompensasi pada dimensi struktur internal. Walaupun dimensi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata, dimensi ini akan berhubungan secara individualdalam bahasa yang bertujuan heuristic (mencari solusi).
sturuktur keluarga akhirnya dievaluasi untuk mengetahui seberapa baik keluarga mampu untuk memenuhi funsgi umum (pentingnya tujuan akhir bagi anggota dan masyarakat). Struktur keluarga dan komunikasi terkait memfasilitasi pencapaian fungsi keluarga. Komunikasi dalam keluarga dapat dipandang sebagai isi pola dan diuraikan sebagai suatu komponen structural. Secara bersamaan, komunikasi didalam keluarga dapat dianggap sebagai interaksi yang beruntun sepanjang waktu dan dikaji sebagai proses. Pada penerapan perspektif ini, perilaku dipandang sama dengan komunikasi. Dalam menjaga perspektif yang dominan ini dalam literature keperawatan keluarga, makalah ini menekankan suatu system perspektif berorientasi pada proses dalam membahas komunikasi keluarga
B. Tujuan
1. Tujuan umum untuk mengetahui tentang komunikasi keluarga
2. Tujuan ksusus
a. Untuk mengetahui tentang penertian komunikasi
b. Untuk mengetahui tentang unsur komunikasi
c. Untuk mengetahui tentang prinsip komunikasi
d. Untuk mengetahui tentang proses komunikasi fungsional
e. Untuk mengetahui tentang proses komunikasi disfungsional
f. Untuk mengetahui tentang pola komunikasi fungsional dalam keluarga
g. Untuk mengetahui tentang pola komunikasi disfungsional dalam keluarga
h. Untuk mengetahui tentang komunikassi dalam keluarga dengan gangguan kesehatan
»» READMORE...
TINJAUAN TEORITIS
A. PENGERTIAN KOMUNIKASI
Komunikasi adalah proses pertukaran perasaan, keinginan, kebutuhan dan pendapat (Mv Cubbin & Dhal, 1985). Galvin dan Brommel (1986), mendefinisikan komunikasi keluarga sebagai suatu simbiosis, proses transaksional menciptakan dan membagi arti dalam keluarga. Seperti halnya setiap orang mempunyai gaya komunikasi yang berbeda, begitu pula setiap keluarga mempunyai gaya dan pola komunikasi yang unik dan berbeda. Komunikasi yang jelas dan fungsional antara keluarga merupakan alat yang penting untuk mempertahankan lingkungan yang kondusif yang diperlukan untuk mengenbangkan perasaan berharga dan harga diri serta menginternalisasikannya. Sebaliknya, komunikasi yang tidak jelas diyakini sebagai penyebab utama fungsi keluarga yang buruk ( Holman,1983; Satir,1983; Satir, Bannem Gerber & Gomori, 1991). Masalah komunikasi yang problematis dalam keluarga terjadi dimana-mana. Watzlawic dan rekan (1967), peneliti komunikasi keluarga memperkirakan bahwa 85% dari semua pesan yang dikirim dalam keluarga adalah salah paham.
B. UNSUR KOMUNIKAS
pola dan proses komunikasi merupakan salah satu proses informasi dalam keluarga yang konsisten dengan kerangka system secara umum. Komunikasi memerlukan pengirim, saluran dan penerima pesan serta interaksi antara pengirim dan penerima. Pengirim adalah orang yang mencoba untuk memindahkan suatu pesan kepada orang lain. Penerima adalah sasaran dari pengirim pesan . bentuk atau saluran adalah rute pesan. Komunikasi diteruskan dari kognisi atau pikiran pengirim melalui ruang ke kognisi penerima. Modalitas komunikasi yang dibahas secara luas di literatur mencakup pembicaraan, tulisan, dan media seperti televisi atau internet. Modalitas komunikasi yang ditulis dalam literature komunikasi interpersonal dan komunikasi keluarga adalah bahasa yang digunakan. Akan tetapi, banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga yang tidak yang tidak dapat (memilih atau tidak) sepenuhnya berpartisipasi secara penuh dalam modalitas komukasi oral atau pendengaran ( mis, ibu yang dapat mendengar dengan anak tunarungu, oaring tua dengan anak yang dapat mendengar, orang tua yang mengalami gangguan pendengaran dengan cucunya.
Interaksi dalam arti yang lebih luas mengacu pada pengiriman dan penerimaan pesan, termasuk respon yang ditimbulkan oleh pesan terhadap penerima dan pengirim. Interksi bersipat dinamik, merupakan perubahan komunikasi secara konstan diantara individu (Watzlawick, Beavin, & Jackson,1976). Pesan yang diawali oleh pengirim selalu didistorsi baik oleh pengirim, maupun penerima. salah satu poenyebab utama distorsi adalah kecemasan diri individu yang berinteraksi, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Penyebab yang biasa terjadi lainnya adalah perbedaan dalam kerangka acuan dari individu yang berinteraksi, karena tidak ada persamaan seperti perbedaan usia, latar belakang etnik atau jenis kelamin. Dalam interaksi sehari-hari anggota keluarga biasanya mengasumsikan bahwa anggota keluarga yang lain mempunyai kerangka acuan yang sama kerena hal ini tidak benar untuk banyak kasus, sehingga kesalahpahaman terjadi.
C. PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI
Watzlawick dan rekan (1967), dalam tulisan seminar mereka tentang komunikasi keluarga, Pragmatis of Human Communication, menetapkan enam prinsip komunikasi yang menjadi dasar untuk memehami proses komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi tersebut adalah:
1. Prinsip pertama dan yang paling terpenting yaitu suatu pernyataan bahwa tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi, karena semua prilaku adalah komunikasi. Pada setiap situasi ketika terdapat dua orang atau lebih, individu mungkin atau tidak mungkin berkomunikasi secara verbal. Dalam konteks ini, komunikasi nonverbal merupakan ekspresi tanpa bahasa seperti membalikkan badan atau mengerutkan kening, tapi bukan merupakan bahasa isyarat.
2. Prinsip kedua dari komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai dua tingkat yaitu informasi (isi) dan perintah (instruksi). Isi yaitu apa yang sebenarnya sedang dikatakan (bahasa verbal) sedangkan instruksi adalah menyampaikan maksud dari pesan (Goldenberg,2000). Isi suatu pesan dapat saja berupa pernyataan sederhana, tetapi mempunyai meta-pesan atau instruksi bergantung pada variabel seperti emosi, dan alur bicara, gerakan dan posisi tubuh serta nada suara.
3. Prinsip ketiga (Watzlawick et al.,1967) berhubungan dengan “ pemberian tanda baca (pungtuasi) “ (Bateson, 1979) atau rangkaian komunikasi. Komunikasi melibatkan transaksi, dan dalam pertukaran tiap respon berisi komunikasi berikutnya, selain riwayat hubunbgan sebelumnya (Hartman & Laird, 1983). Komunikasi melayani sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan dan proses penataan diri dlam keluarga.
4. Prinsip komunikasi yang keempat diuraikan oleh Watzlick dan rekannya (1979) yaitu terdapat dua tipe komunikasi yaitu digital dan analogik. Komunikasi digital adal;ah komunikasi verbal ( bahasa isyarat) yang pada dasrnya menggunakan kata dengan pemahaman arti yang sama. Jenis komunikasi yang kedua, analogik yaitu ide atau suatu hal yang dikomunikasikan, dikirim secara nonverbal dan sikap yang representative (Hrtman & Laird, 1983). Komunikasi analogik dikenal sebagai bahasa tubuh, ekspresi tubuh, ekspresi wajah, irama dan nada kata yang diucapkan (isyarat) berbagai manifestasi nonverbal lainnya (non-bahasa)byang dapat dilakukan oleh seseorang( watzlick et al, hal 62).
5. Prinsip komunikasi kelima diuraikan oleh kelompok yang sama dari beberapa ahli teori komunikasi keluarga (Watzlick, Beavin, & Jackson, 1967) yang disebut prinsip redundasi (kemubaziran). Prinsip ini merupakan dasr pengembangan penelitian keluarga yang menggunakan keterbatasan pengamatan interaksi keluarga sehingga dapat memberikan penghayatan yang valid kedalam pola umum komunikasi
6. Prinsip komunikasi yang keenam diuraikan oleh Batson dan rekan (1963) adalah semua interaksi komunikasi yang simetris atau komplementer. Polka komunikasi simetris, prilaku pelaku bercermin pada prilaku pelaku interaksi yang lainnya. Dalam komunikasi komplementer, prilaku seorang pelaku interksi melengkapi prilaku pelaku interaksi lainnya. Jika satu dari dua tipe komunikasi tersebut digunakan secara konsisten dalam hubungan keluarga, tipe komunikasi ini mencerminkan nilai dan peran serta pengaturan kekuasaan keluarga.
D. PROSES KOMUNIKASI FUNGSIONAL
Menurut sebagian besar terpi keluarga, komunikasi fungsional dipandang sebagia landasan keberhasilan, keluarga yang sehat (Watzlick & Goldberg, 2000) dan komunikasi fungsional didefinisikan sebagai pengiriman dan penerima pesan baik isi maupun tingkat instruksi pesan yang lansung dan jelas (Sells,1973), serta sebagi sasaran antara isi dan tingkat instruksi. Dengan kata lain komunikasi fungsional dan sehat dalam suatu keluarga memerlukan pengirim untuk mengirimkan maksud pesan melalui saluran yang reltif jelas dan penerima pesan mempunyai pemahaman arti yang sama dengfan apa yang dimaksud oleh pengirim (Sells). Proses komunikasi fungsional terdiri dari beberapa unsur, antara lain :
1. Pengiriman Fungsional
Satir (1967) menjelaskan bahwa pengiriman yang berkomunikasi secara fungsional dapat menyatakan maksudnya dengan tegas dan jelas, mengklarifikasi dan mengualifikasi apa yang ia katakan, meminta umpan balik dan terbuka terhadap umpan balik.
a. Menyatakan kasus dengan tegas dan jelas
Salah satu landasan untuk secara tegas menyatakan maksud seseorang adalah penggunaan komunikasi yang selaras pada tingkat isi dan instruksi (satir,1975).
b. Intensitas dn keterbukaan.
Intensitas berkenaan dengan kemampuan pengirim dalam mengkomunikasikan persepsi internal dari perasaan, keinginan,dan kebutuhan secara efektif dengan intensitas yang sama dengan persepsi internal yang dialaminya. Agar terbuka, pengirim fungsional menginformasikan kepada penerima tentang keseriusan pesan dengan mengatakan bagaimana penerima seharusnya merespon pesan tersebut.
c. Mengklarifikasi dan mengualifikasi pesan
Karakteristik penting kedua dari komunikasi yang fungsional menurut Satir adalah pernyataan klarifikaasi daan kualifikaasi. Pernyataan tersebut memungkinkan pengirim untuk lebih spesifik dan memastikan persepsinya terhadap kenyataan dengan persepsi orang lain.
d. Meminta umpan balik
Unsur ketiga dari pengirim fungsional adalah meminta umpan balik, yang memungkinkan ia untuk memverifikasi apakah pesan diterima secara akurat, dan memungkinkan pengirim untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi maksud.
e. Terbuka terhadap umpan balik
Pengirim yang terbuka terhadap umpan balik akan menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, bereaksi tanpa defensive, dan mencoba untuk memahami. Agar mengerti pengirim harus mengetahui validitas pandangan penerima. Jadi dengan meminta kritik yang lebih spesifik atau pernyataan “memastikan”, pengirim menunjukkan penerimaannya dan minatnya terhadap umpan balik.
2. Penerima Fungsional
Penerima fungsional mencoba untuk membuat pengkajian maksud suatu pesa secara akurat. Dengan melakukan ini, mereka akan lebih baik mempertimbangkan arti pesan dengan benar dan dapat lebih tepat mengkaji sikap dan maksud pengirim, serta perasaan yang diekspresikan dalam metakomunikasi. Menurut Anderson (1972), penerima fungsional mencoba untuk memahami pesan secara penuh sebelum mengevaluasi.ini berarti bahwa terdapat analisis motivasi dan metakomunikasi, serta isi. Informasi baru, diperiksa dengan informasi yang sudah ada, dan keputusan untuk bertindak secara seksama dioertimbangkan. Mendengar secara efektif, member umpan balik, dan memvalidasi tiga tekhnik komunikasi yang memungkinkan penerima untuk memahami dan merespons pesan pengirim sepenuhnya.
a. Mendengarkan
Kemampuan untuk mendengar secara efektif merupakan kualitas terpenting yang dimiliki oleh penerima fungsional. Mendengarkan secara efektif berarti memfokuskan perhstisn penuh pada seseorang terhadap apa yang sedang dikomunikasikannya dan menutup semua hal yang aakan merusak pesan. Penerima secara penuh memperhatikan pesan lengkap dari pengirim bukan menyalahartikan arti dari suatu pesan. Pendengar pasif merespons dengan ekspresi datar dan tampak tidak peduli sedangkan pendengar aktif dengan sikap mengomunikasikan secara aktif bahwa ia mendengarkan. Mengajukan pertanyaan merupakan bagian penting dari mendengarkan aktif (Gottman, Notarius, Gonso dan Markman, 1977). Mendengarkan secara aktif berarti menjadi empati, berpikir tentang kebutuhan, dan keinginan orang lain, serta menghindarkan terjadinya gangguan alur komunikasi pengirim.
b. Memberikan umpan baliki
Karakteristik utam kedua dari penerima funbgsional adalah memberikan umpan balik kepada pengirim yang memberitahu pengirim bagaimana penerima menafsirkan pesan. Pernyataan ini mendorong pengirim untuk menggali lebih lengkap. Umpan balik juga dapat melalui suatu proses keterkaitan, yaitu penerima membuat suatu hubungan antara pengalaman pribadi terdahulu (Gottman et.al, 1877) atau kejadian terkait dengan komunikasi pengirim.
c. Member validasi
Dalam menggunakan validasi penerima menyampaikan pemahamannya terhadap pemikiran dan perasaan pengirim. Validasi tidak berarti penerima setuju dengan pesan yang dikomunikasikan pengirim, tetapi menunjukan penerimaan atas pesan tersebut berharga.
E. PROSES KOMUKASI DISFUNGSIONAL
1. Pengirim Disfungsional
Komunikasi pengirim disfungsional sering tidak efektif pada satu atau lebih karakteristik dasar dari pengirim fungsional. Dalam menyatakan kasus, mengklarifikasi dan mengkulifikasi, dalam menguraikan dan keterbukaan terhadap umpan balik. Penerima sering kali ditinggalkan dalam kebingungan dan harus menebak apa yang menjadi pemikiran atau perasaan pengirim pesan. Komunikasi pengirim disfungsional dapat bersifat aktif atau defensif secara pasif serta sering menuntut untuk mendapatkan umpan balik yang jelas dari penerima. Komunikasi yang tidak sehat terdiri dari :
a. Membuat asumsi
Ketika asumsi dibuat, pengim mengandalkan apa yang penerima rasakan atau pikiran tentang suatu peristiwa atau seseorang tanpa memvalidasi persepsinya. Pengirim disfungsional biasanya tidak menyadari asumsi yang mereka buat, ia jarang mengklarifikasi isi atau maksud pesaan sehingga dapat terjadi distorsi pesan. Apabila hal ini terjadi, dapat menimbulkan kemarahan pada penerima yang diberi pesan, yang pendapat serta perasaan yant tidak dianggap.
b. Mengekspresika perasaan secara tidak jelas
Tipe lain dari komunikasi disfungsional oleh pengirim adalah pengungkapan perasaan tidak jelas, karena takut ditolak, ekspresi perasaan pengirim dilakukan dengan sikap terselubung dan sama sekali tertutup. Komunikasi tidak jelas adalah “sangat beralasan” (Satir, 1991) apabila kata-kata pengirim tidak ada hubunganya dengan apa yang dirasakan. Pesan dinyatakan dengan cara yang tidak emosional. Berdiam diri merupakan kasus lain tentang pengungkapan perasaan tidak jelas. Pengirim merasa mudah tersinggung terhadap penerima yang tetap tidak mengungkapkan kemarahannya secara terbuka atau mengalihkan perasaannya ke orang atau benda lain.
c. Membuat respon yang menghakimi
Respon yang menhakimi adalah komunikasi disfungsional yang ditandai dengan kecenderungan untuk konstan untuk menbgevaluasi pesan yang menggunakan system nilai pengirim. Pernyataan yang menghakimi selalu mengandung moral tambahan. Pesan pernyataan tersebut jelas bagi penerima bahwa pengirim pesan mengevaluasi nilai dari pesan orang lain sebagai “benar”, atau “salah”, “baik” atau “buruk”, “normal” atau “tidak normal”.
d. Ketidakmampuan untuk mendefinisika kebutuhan sendiri
Pengirim disfungsional tidak hanya tidak mampu untuk menekspresikan kebutuhangnya. Namun juga karena takut ditolak menjadi tidak mampu mendefenisikan prilaku yang ia harapkan dari penerima untuk memenuhi kebutahan mereka.sering kali pengirim disfungsiopnal tidak sadar merasa tidak berharga, tidak berhak untuk mengungkapkan kebutuhan atau berharap kebutuhan pribadinya akan dipenuhi.
e. Komunikasi yang tidak sesuai
Penampilan komunikasi yang tidak sesuai merupakan jenis komunikasi yang disfungsional dan terjadi apabila dua pesan yang bertentangan atau lebih secara serentak dikiri (Goldenberg, 2000). Penerima ditinggalkan dengan teka-teki tentang bagaimana harus merespon. Dalam kasus ketidaksesuaian pesan verbal dan nonverbal, dua atau lebih pesan literal dikirim secara secara serentak bertentangan satu sama lain. Pada ketidaksesuaian verbal nonverbal pengirim mengkomunikasikan suatu pesan secara verbal, namun melakukan metakomunikasi nonverbalyang bertentangan dengan pesan verbal. Ini biasanya diketahuinsebagai “pesan campuran”, misalnya “ saya tidak marah pada anda” diucapakan dengan keras, nada suara tinggi dengan tangan menggempal.
2. Penerima Disfungsional
Jika penerima disfungsional, terjadi komunikasi yang terputus karena pesan tidak diterima sebagaimana dimaksud, karena kegagalan penerima untuk mendengarkan, atau menggunakan diskualifikasi. Merespon secara ofensif, gagal menggali pesan pengirim, gagal memvalidasipesan, merupakan karakterstik disfungsional lainnya.
a. Gagal untuk mendengarkan
Dalam kasus gagal untuk mendengarkan, suatu pesan dikirim, namun penerima tidak memperhatikan atau mendengarkan pesan tersebut. Terdapat beberapa alasan terjadinya kegagalan untuk mendengarkan, berkisar dari tidak ingin memerhatikan hingga tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Hal ini biasanya terjadi karena distraksi, seperti bising, waktu yang tidak tepat, kecemasan tinggi, atau hanya karena gangguan pendengaran.
b. Menggunakan diskualifikasi
Penerima disfungsional dapat menerapkan pengelakkan untuk mendiskualifikasi suatu pesan dengan menghindari isu penting. Diskualifikasi adalah respon tidak langsung yang memungkinkan penerima untuk tidak menyetujui pesan tanpa memungkinkan penerima untuk tidak menyetujui pesan tanpa benar-benar tidak menyetujuinya.
c. Menghina
Sikap ofensif komunikasi menunjukkan bahwa penerima pesan bereaksi secara negatif, seperti sedang terancam. Penerima tampak bereaksi secara defensif terhadap pesan yang mengasumsikan sikap oposisi dan mengambil posisi menyerang. Pernyataan dan permintaan dibuat dengan konsisten dengan sikap negatif atau dengan harapan yang negatif.
d. Gagal menggali pesan pengirim
Untuk mengklarifikasi maksud atau arti dari suatu pesan, penerima fungsional mencari penjelasan lebih lanjut. Sebaliknya, penerima disfungsional menggunkan respon tanpa menggali, seperti membuata asumsi , memberikan saran yang prematur, atau memutuskan komunikasi.
e. Gagal memvalidasi pesan
Validasi berkenaan dengan penyampaian penerimaan penerima. Oleh karena itu, kurangnya validasi menyiratkan bahwa penerima dapat merespon secara netral atau mendistorsi dan menyalahtafsirkan pesan. Mengasumsikan bukan mengklarifikasi pemikiran pengirim adalah suatu contoh kurangnya validasi.
3. Pengirim dan Penerima Disfungsional
Dua jenis urutan intearksi komunikasi yang tidak sehat, melibatkan baik pengirim maupun penerima, juga secara luas didiskusikan dalam literatur komunikasi. Komunikasi yang tidak sehat merupakan kominikasi yang mencerminkan pembicaraan “ parallel” yang menunjukan ketidakmampuan untuk memfokuskan pada suatu isu.
Dalam pembicraan parallel, setiap individu dalam interaksi secara konstan menyatakan kembali isunya tanpa betul-beetul mendengarkan pandangan orang lain atau mengenali kebutuhan orang lain. Orang yang berinteraksi disfungsional, mungkin tidak mampu untuk memfokuskan pada satu isu. Tiap individu melantur dari satu isu ke isu lain bukannya menyelesaikan satu masalah atau meminta suatu pengungkapan.
F. POLA KOMUNIKASI FUNGSIONAL DALAM KELUARGA
1. Berkomunikasi Secara Jelas dan Selaras
Pola sebagian nkeluarga yang sehat, terdapat keselarasan komunikasi diantara anggota keluarga. Keselarasan merupakan bangunan kunci dalam model komunikasi dan pertumbuhan menurut satir. Keselarasan adalah suatun keadaan dan cara berkomunikasi dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika keluarga berkomunikasi dengan selarad terdapat konsistensi dengan selaras terdapat konsistensi anatara tingkat isi dan instruksi kominikasi. Apa yang sedang diucapkan, sama dengan isi pesan. Kat-kata yang diucapkan, perasaan yang kita ekspresikan, dan prilaku yang kita tampilkan semuanya konsisten. Komunikasi pada kelurga yang sehat merupakan suatu proses yang sangat dinamis dan saling timbal balik. Pesan tidak hanya dikirim dan diterima.
2. Komunikasi Emosional
Komunikasi emosional berkaitan dengan ekspresi emosi dan persaan dari persaan marah, terluka, sedih, cemburu hingga bahagia, kasih sayingdan kemesraan (Wright & Leahey, 2000). Pada keluarga fungsional perasaan anggota keluarga ddiekspresikan. Komunikasi afektif pesan verbal dan nonverbal dari caring, sikapfisik sentuhan, belaian, menggandeng dan memandang sangat penting, ekspresi fisik dari kaisih saying pada kehidupan awal bayi dan anak-anak penting untuk perkembangan respon afektif yang normal. Pola komunikasi afeksi verbal menjadi lebih nyata dalam menyampaikan pesan afeksional, walaupun pola mungkin beragam dengan warisan kebudayaan individu.
3. Area Komunikasi Yang Terbuka dan Keterbukaan diri
Keluarga dengan pola komunikasi fungsional menghargai keterbukaan, saling menghargai perasaan, pikiran, kepedulian, spontanitas, autentik dan keterbukaan diri. Selanjutnya keluarga ini mampu mendiskusikan bidang kehidupan isu personal, social, dan kepedulian serta tidak takut pada konflik. Area ini disebut komunikasi terbuka. Dengan rasa hormat terhadap keterbukaan diri. Satir (1972) menegaskan bahwa anggota keluarga yant terus terang dan jujur antar satu dengan yang lainnya adalah orang-orang yang merasa yakin untuk mempertaruhkan interaksi yang berarti dan cenderung untuk menghargai keterbukaan diri (mengungkapkan keterbukaan pemikiran dan persaan akrab).
4. Hirarki Kekuasaan dan Peraturan Keluarga
System keluarga yang berlandaskan pada hirarki kekuasaan dan komunikai mengandung komando atau perintah secara umum mengalir kebawah dalam jaringan komunikasi keluarga. Interaksi fungsional dalam hirarki kekuasaan terjadi apabila kekuasaan terdistribusi menurut kebutuhan perkembangan anggota keluarga (Minuchin, 1974). Apabila kekuasaan diterpkan menurut kemampuan dan sumber anggota keluarga serta sesuai dengan ketentuan kebudayaan dari suatu hubungan kekuasaan keluarga.
5. Konflik dan Resolusi Konflik Keluarga
Konflik verbal merupakan bagian rutin dalam interaksi keluarga normal. Literature konflik keluarga menunjukkan bahwa keluraga yang sehat tanpak mampu mengatasi konflik dan memetik mamfaat yang positif, tetapi tidak terlalu banyak konflik yang dapat mengganggu hubungan keluarga. Resolusi konflik merupakan tugas interaksi yang vital dalam suatu keluarga (Vuchinich,1987). Orang dewasa dalam kelurga perlu belajar untuk mengalami konflik konstruktif. Walaupun orang dewasa menyelesaikan konflik dengan berbagai cara , resolusi konflik yang fungsional terjadi apabila konflik tersebut dibahas secara terbuka dan strategi diterpkan untuk menyelesaikan konflik dan ketika orang tua secara tepat menggunakan kewenangan mereka untuk mengakhiri konflik.
G. POLA KOMUNIKASI DISFUNGSIONAL DALAM KELUARGA
Komunikasi disfungsional didefinisikan sebagai transmisi tidak jelas atau tidak langsung serta permintaan dari salah satu keluarga. Isi dan instruksi deari pesan dan ketidaksesuaian antara tingkat isi dan instruksi dari pesan. Transmisi tidak lansung dari suatu pesan berkenaan dari pesan yang dibelokkan dari saran yang seharusnya kepada orang lain dalam keluarga. Transmisi langsung dari suatu pesan berarti pesan mengenai sasaran yang sesuai. Tiga pola komunikasi yang terkait terus menerus menyebabkan harga diri rendah adalah egasentris, kebutuhan akan persetujuan secara total dan kurangnya empati.
1. Egosentris
Individu memfokuskan pada kebutuhan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain, perasaan atau perspektif yang mencirikan komunikasi egosentris. Dengan kata lain, anggota keluarga yang egosentris mencari sesuatu dari orang lain untuk memenuhu kebutuhan mereka. Apabila individu tersebut harus memberikan sesuatu, maka mereka akan melakukan dengan keengganan, dan rasa permusuhan,defensive atau sikap pengorbanan diri, jadi tawar-menawar atau negosiasi secara efektif sulit dilakukan, karena seseorang yang egosentris meyakini bahwa mereka tidak boleh kalah untuk sekecil apapun yang mereka berikan.
2. Kebutuhan Mendapatkan Persetujuan Total
Nilai keluarga tentang mempertahankan persetujuan total dan menghindari konflik berawal ketika seseorang dewasa atau menikah menetukan bahwa mereka berada satu sama lain, walaupun perbedaan yang pasti mungkin sulit untuk dijelaskan seperti yang diekspresikan dalam pendapat, kebiasaan, kesukaan atauhrapan mungkin terlihat sebagai ancaman kerena ia dapat mengarah pada ketidaksetujuan dan kesadaran bahwa mereka merupakan dua individu yang terpisah
3. Kurang Empati
Keluarga yang egosentris tidak dapat menteloransi perbedaan dan tidak akan mengenal akibat dari pemikiran, persaan dan perilaku mereka sendiri terhadap anggota keluarga yang lain. Mereka sangat terbenam dalam pemenuhan kebutuhan mereka sendiri saja bahwa mereka tidak mampu untuk berempati. Dibalik ketidakpedulian ini, individu dapat menderia akibat perasaan tidak berdaya. Tidak saja mereka tidak menghargai diri mereka sendiri tapi mereka juga tidak menghargai oaring lain. Hal ini menimbulakan suasana tegang, ketakutan atau menyalahkan. Kondisi ini terlihat pada komunikasi yang lebih membingungkan, samar, tidak langsung, terselubung dan defensif bukan memperlihatkan keterbukaan, kejelasan dan kejujuran.
4. Area Komunikasi Yang Tertutup
Keluarga yang fungsional memiliki area komunikasi yang terbuka, keluarga yang sedikit fungsional sering kali menunjukkan area komunikasi yang semakin tertutup. Keluarga tidak mempunyai peraturan tidak tertulis tentang subjek apa yang disetujui atau tidak disetujui untuk dibahas. Peraturan tidak tertulis ini secara nyata terlihat ketika anggota keluarga melanggar peraturan dengan membahas subjek yang tidak disetujui atau mengungkapkan perasaan yang terlarang.
H. KOMUNIKASI DALAM KELUARGA DENGAN GANGGUAN KESEHATAN
Istilah gangguan kesehatan berkenaan dengan setiap perubahan yang mempengaruhi proses kehidupan klien (psikologis, fisiologis, social budaya, perkembangan dan spiritual) (Carpeniyo, 2000). Gangguan dalam status kesehatan sering kali mencakup penyakit kronis dan penyakit yang mengancam kehidupan serta ketidakmampuan fisik dan mentak akut atau kronik, namun dapat juga meliputi perubahan dalam area ksehatan lainnya. Pola Temuan penelitian tentang adaptasi keluarga terhadap penyakit kronik dan mengancam kehidupan secara konsisten menunjukkan bahwea factor sentral dalam fungsi keluarga yang sehat adalah terdapatnya keterbukaan, kejujuran, dan komunukiasi yang jelas dalam mengatasi pengalaman kesehatan yang menimbulkan stres serta isu terkait lainnya (Khan,1990;Spinetta & Deasy-Spineta, 1981). Jiak keluarga tidak membahas isu penting yang dihadapi mereka, akan menyababkan jarak emosi dalam hubungan keluarga, dan meningkatnya stress keluarga (Friedman, 1985; Walsh,1998). Sters yang meningkat mempengaruhi hubungan keluarga dan kesehatan keluarga serta anggotanya (Hoffer, 1989).
1. Area Pengkajian
Pernyataan berikut ini harus dipertimbangkan ketika menganalisis pola komunikasi keluarga.
a. Dalam mengobservasi keluarga secara utuh atau serangkaian hubungan keluarga, sejauh mana pola komunikasi fungsional dan disfungsional yang digunakan ?. diagram pola komunikasi sirkular yang terjadi berulang. Selain membuat diagram pola komunikasi sirkular, prilaku spesifik berikut ini harus dikaji:
1) Seberapa tegas dan jelas anggota menyatakan kebutuhan dan perasaan interaksi?
2) Sejauh mana anggota menggunakan klerifikasi dan kualifikasi dalam interaksi?
3) Apakah anggoata keluarga mendapatkan dan merespon umpan balik secara baik, atau mereka secara umumtidak mendorong adanya umpan balik dan penggalian tentang suatu isu?
4) Sebera baik anggota keluarga mendengarkan dan memperhatikan ketika berkomunikasi?
5) Apakah anggota mencari validasi satu sama lain?
6) Sejauh mana anggota menggunakan asumsi dan pernyataan yang bersifat menghakimi dalam interksi?
7) Apakah anggota berinterksi dengan sikap menhina terhadap pesan?
8) Seberapa sering diskualifikasi digunakan?
b. Bagimana pesan emosional disampaikan dalam keluarga dan subsistem keluarga?
1) Sebera sering pesan emosional disampaikan?
2) Jenis emosi apa yang dikirimkan ke subsistem keluarga? Apakah emosi negatif, positif, atau kedua emosi yang dikirimkan?
c. Bagaimana frekuensi dan kualitas komunikasi didalam jaringan komunikasi dan rangkaian hubungan kekeluargaan?
1) Bagaimana cara/sikap anggota kelurga (suami-istri, ayah-anak,anak-anak) saling berkomunikasi?
2) Bagaimana pola pesan penting yang biasanya? Apakah terdapat perantar?
3) Apakah pesan sesuai dengan perkembangan usia anggota?
d. Apakah pesan penting keluarga sesuai dengan isi instruksi ? apabila tidak, siapa yang menunjukkan ketidaksesuaian tersebut?
e. Jenis proses disfungsional apa yang terdapat dalam pola komunikasi keluarga?
f. Apa isu penting dari personal/keluarga yang terbuka dan tertutup untuk dibahas?
g. Bagiman factor-faktor berikut mempengaruhi komunikasi keluarga?
1) Konteks/situasi
2) Tahap siklus kehidupan kelurga
3) Latar belakakang etnik kelurga
4) Bagaimana gender dalam keluarga
5) Bentuk keluarga
6) Status sosioekonomi keluarga
7) Minibudaya unik keluarga
2. Diagnosa Keperawatan Keluarga
Masalah komunikasi keluarga merupakan diagnosis keperawatn keluarga yang sangat bermakna, Nort American Diagnosis Assosiation (NANDA) belum mengidentifikasi diagnosis komunikasi yang berorientasi keluarga. NANDA menggunakan perilaku komunikasi sebagai bagian dari pendefisian karakteristik pada beberapa diagnosis mereka;seperti proses berduka disfungsional salah satu diagnosis keperawatn yang terdapat dalam daftar NANDA adalah “hanbatan komunikasi verbal”, yang berfokus pada klien individu yang tidak mampu untuk berkomunikasi secara verbal. Giger & Davidhizar (1995) menegaskan bahwa ”hambatan komunikasi verbal” tidak mempertimbangkan kjebudayaan klien sehingga secara kebuyaan tidak relevan dengan diagnosis keperawatan.
3. Intervensi Keperawatan Keperawatan
Intervensi keperawatn keluarga dalam keluarga dalam area komunikasi terutama melibatkan pendidikan kesehatan dan konseling, serta kolaborasi sekunder, membuat kontrak, dan merujuk ke kelompok swa-bantu, organisasi komunitas, dan klinik atau kantor terapi keluarga. Model peran juga berperan tipe pemberian pendidikan kesehatan yang penting. Model peran melalui observasi anggota keluarga mengenai tenaga kesehatan keluarga dan bagaimana mereka berkomunikasi selam situasi interaksi yang berbeda bahwa mereka belajar meniru perilaku komunikasi yang sehat.
Konsling dibidang komunikasi keluarga melibatkan dorongan dan dukungan keluarga dalam upaya mereka untuk meningkatkan komunikasi diantara mereka sendiri. Perawat keluarga adalah sebagai fasilitator proses kelompok dan sebagi narasumber. Wright dan Leahey (2000) menklasifikan tentang tiga intervensi keluarga secara lansung (berfokus pada tingkat kognitif, afektif, dan perilaku dari fungsi) membantu dalam pengorganisasian srategi komunikasispesifik yang dapat diterapkan, strategi intervensi dalam masing-masing ketiga domain meliputi pendidikan kesehatan dan konsling.
a. Intervensi keperawatn keluarga dengan focus kognitif memberikan atau ide baru tentang komunikasi. Informasi adalah opendidikan yang dirancang untuk mendorong penyelesaian masalah keluarga. Apakah anggota mengubah perilaku komunikasi mereka pertama sangat bergantung pada bagiamana mereka mempersepsikan masalah. Wright & Laehey (2000) menegaskan peran penting dari persepsi dan keyakinan.
b. Intervensi dalam area afektif diarahkan pada perubahan ekspresi emosi anggota keluarga baik dengan meningkatkan maupun menurunkan tingkat komunikasi emosional dan modifikasi mutu komunikasi emosional. Tujuan keperawatan spesifik didalam konteks kebudayaan keluarga, membantu anggota keluarga mengekspresikan dan membagi perasaan mereka satu sama lain sehingga:
1) Kebutuhan emosi mereka dapat disampaikan dan ditanggapi dengan lebih baik.
2) Terjadi komunikasi yang lebih selaras dan jelas
3) Upaya penyelesaian masalah keluarga difasilitasi.
c. Intervensi keperawatan keluarga berfokus pada perilaku, perubahan perilaku menstimulasi perubahan dalam persepsi “realitas” anggota keluarga dan persepsi menstimulasi perubahan perilaku (proses sirkular, rekursif). Oleh karena itu, ketika perawat keluarga menolong anggota keluarga belajar cara komunikasi yang lebih sehat. Ia juga akan membantu anggota keluarga untuk mengubah persepsi mereka atau membangun realitas tentang suatu situasi.
Intervensi pendidikan kesehatan dan konsling dirancang untuk mengubah komunikasi keluarga meliputi;
a. Mengidentifikasi keinginan perubahan perilaku spesifik anggota keluarga dan menyusun rencana kolaboratif untuk suatu perubahan
b. Mengakui, mendukung, dan membimbing anggota keluarga ketika mereka mulai mencoba untuk berkomunikasi secar jelas dan selaras.
c. Memantau perubhan perilaku yang telah menjadi sasran sejak pertemuan terdahulu. Tanyakan bagimana perilaku komunikassi yang baru, apakah ada masalah yang terjadi, serta jika mereka mempunyai pertanyaan atau hal penting tentang perubahan tersebut.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Komunikasi keluarga dikonsepsulisasikan sebagai salah satu dari empat dimensi struktur dan system keluarga beserta kekuasaan, peran dan pengambilan keputusan, serta dimensi struktur nilai. Struktur keluarga dan proses komunikasi terkait memfasilitasi pencapaian fungsi keluarga. Selain itu, pola komunikasi dalam sisten keluarga mencerminkan peran dan hubungan anggota keluarga. Komunikasi memerlukan pengirim, saluran dan penerima pesan serta interaksi antara pengirim dan penerima. Pengirim adalah seorang yang mencoba untuk memindahkan suatu pesan yang dikirimkan dan saliran merupakan perjalanan atau rute pesan.
Enam prinsip komunikasi adalah: (1) tidak mungkin untuk tidak berkomuniasi; semua perilaku adalah komunikasi; (2) komunikasi mempunyai dua tingkat yaitu komando dan informasi; (3) komunikasi melibatkan proses transaksional dan tiap anggota keluarga mempunyai “pungtuasi” peristiwa interaksi mereka sendiri; (4) ada dua tipe komunikasi yaitu digital dan analogik; (5) interaksi keluarga adalah redundansi yaitu interaksi keluarga dalam kisaran perbatas dari urutan perilaku berulang-ulang; (6) semua interaksi komunikasi simetris atau saling melengkapi.
Komunikasi fungsional didefinisikan sebagi pengiriman dan penerimaan tingkat isi dan instruksi dari tiap pesan yang jelas dan langsung begitu pula keselarsan antara tingkat isi dan instruksi. Komunikasi disfungsional adalah pengiriman dan penerimaan isi dan instruksi pesan yang tidak jelas dan tidak langsung atau tidak ada kesesuaian antara tingkat isi dan instruksi.
Karakteristik keluarga yang sehat adalah komunikasi yang jelas dan kemampuan untuk saling mendengarkan. Komunikasi yang baik diperlukan untuk membina dan memlihara hubungan penuh rasa cinta. Factor sentral dalam fungsi keluarga yang sehat ketika seseorang mengalami perubahan kesehatan adalah komunikasi yang terbuka, jujur. Jelas dalam mengatasi pengalamankesehatan yang menimbulkan sters serta isu terkait. Pedoman pengkajian komunikasi keluarga digambarkan sebagai pedoman untuk diagnosis dan intervensi keperawatan untuk memfasilitasi pola komunikasi sehat keluarga.
B. Saran
Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa menggunakan makalah ini dan juga menjadikannya sebagai pedoman dalam memberikan intervensi keperawatan tentang komunikasi pada keluarga dengan gangguan masalah kesehatan dan dalam memberikan pendidikan serta konslinguntuk merubah perilaku .
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan senantiasa mengaharapkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Tak lupa salawat dan salam bagi junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis masih diberi kesehatan dan umur sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul ”KOMUNIKASI KELUARGA” yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keperawatan Keluarga. Dalam penyusunan makalah ini penulis sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan mungkin jauh dari sempurna, begitupun dengan makalah ini oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta kepada pembaca pada umumnya.
Pekanbaru, April 2011
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komunikasi keluarga dinyatakan dalam bentuk konsep sebagai salah satu dari empat dimensi struktur system keluarga, kekuasaan, pengambilan keputusan dan struktur peran serta norma dan nilai keluarga. Dimensi tersebut saling berhubungan dan saling bergantung secara erat. Karena keluarga merupakan suatu sistem social, terdapat interaksi dan umpsn balik bersinambungan antar lingkungan internal dan eksternal. Perubahan pada satu bagian system keluarga pada umumnya diikuti dengan perubahan kompensasi pada dimensi struktur internal. Walaupun dimensi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata, dimensi ini akan berhubungan secara individualdalam bahasa yang bertujuan heuristic (mencari solusi).
sturuktur keluarga akhirnya dievaluasi untuk mengetahui seberapa baik keluarga mampu untuk memenuhi funsgi umum (pentingnya tujuan akhir bagi anggota dan masyarakat). Struktur keluarga dan komunikasi terkait memfasilitasi pencapaian fungsi keluarga. Komunikasi dalam keluarga dapat dipandang sebagai isi pola dan diuraikan sebagai suatu komponen structural. Secara bersamaan, komunikasi didalam keluarga dapat dianggap sebagai interaksi yang beruntun sepanjang waktu dan dikaji sebagai proses. Pada penerapan perspektif ini, perilaku dipandang sama dengan komunikasi. Dalam menjaga perspektif yang dominan ini dalam literature keperawatan keluarga, makalah ini menekankan suatu system perspektif berorientasi pada proses dalam membahas komunikasi keluarga
B. Tujuan
1. Tujuan umum untuk mengetahui tentang komunikasi keluarga
2. Tujuan ksusus
a. Untuk mengetahui tentang penertian komunikasi
b. Untuk mengetahui tentang unsur komunikasi
c. Untuk mengetahui tentang prinsip komunikasi
d. Untuk mengetahui tentang proses komunikasi fungsional
e. Untuk mengetahui tentang proses komunikasi disfungsional
f. Untuk mengetahui tentang pola komunikasi fungsional dalam keluarga
g. Untuk mengetahui tentang pola komunikasi disfungsional dalam keluarga
h. Untuk mengetahui tentang komunikassi dalam keluarga dengan gangguan kesehatan